Jakarta seperti mendapat julukan baru sebagai kota multikrisis. Problematikanya
semakin menjepit penduduk Jakarta dengan pilihan-pilihan pahit: banjir, kemacetan, penurunan permukaan tanah, krisis air bersih, sampah, hingga urbanisasi.
Dilema Jakarta adalah dilema Republik. Gagal menata Jakarta bisa menjadi indikasi kegagalan menata kota-kota lain yang hasrat hedonisnya tidak jauh berbeda dengan Jakarta. Kita seperti menghadapi lingkaran buntu, obesitas kota yang sudah terlalu berat dengan berbagai penyakit kronis. Akibatnya, sulit mencari solusi yang cerdas.
Fakta dan realitas sejarah perkembangan kota harus dilihat sebagai dasar analisis untuk membaca penyimpangan yang terjadi saat ini. Tidak mudah menyalahkan sistem jika kita tidak mengkaji apakah kota ini pernah membuat mekanisme perencanaan kota yang konsisten.
Pasca-kemerdekaan, Jakarta sebenarnya tidak pernah seutuhnya mengimplementasikan rencana kota. Masterplan pertama disiapkan tahun 1952, tetapi tak pernah direalisasikan, menyusul masterplan 1965-1985 dan masterplan 1985-2005 guna mengatasi pertumbuhan kota yang pesat. Terakhir adalah Masterplan Jakarta 2000-2010 yang semakin menunjukkan penyimpangan pemanfaatan ruang.
Indikasi penyimpangan menunjukkan pertumbuhan kota yang begitu cepat sehingga para perencana dan pengelola kota kurang mampu mengontrol perkembangan. Perhatian lebih terfokus pada segitiga emas Kuningan-Thamrin-Sudirman, pantura Jakarta, dan permukiman elite swasta serta kawasan sentra ekonomi primer.
Infrastruktur kota lebih fokus pada proyek-proyek yang menarik dari sudut pandang ekonomi dan politik (pencitraan), seperti jalan tol dalam kota, Banjir Kanal Timur, dan transjakarta. Terjadilah pengabaian terhadap hal-hal yang bersifat mikro, seperti pemeliharaan drainase kota. Akibatnya, dimensi drainase tetap sama seperti kondisi 30 tahun lalu, padahal kota dan penduduk terus bertambah besar.
Sinergi antarprogram dan pelaku kepentingan minim implementasi. Ego sektoral dan ego kepentingan pemilik modal telah menggiring massa ke arah bunuh diri ide. Tidak muncul daya kreativitas baru karena semua sudah terkontaminasi racun hedonisme dan konsumerisme (Kompas, 2006). Kita tidak mengindahkan lagi aturan, hak asasi manusia, pluralisme, dan etika.
Kemacetan telah membuat frustrasi para pemakai jalan raya di kawasan inti dan penyangga kota. Pemborosan energi, waktu, dan polusi semakin meningkat dan semua menggunakan bahan bakar bersubsidi. Perkiraan ”biaya” kemacetan mencapai Rp 48 triliun per tahun.
Dari total penduduk Jakarta, 63 persen menghabiskan 20-30 persen pendapatan hanya untuk biaya transportasi. Kerugian ekonomi akibat inefisiensi transportasi mencapai Rp 5,5 triliun per tahun dan akibat kualitas udara buruk Rp 2,8 triliun per tahun.
Semua kerugian itu akibat tidak bersinerginya tiga komponen sistem perencanaan transportasi sehingga terjadi kegagalan sistem. Komponen pertama adalah perencanaan sistem kegiatan, yakni bagaimana merencanakan pusat-pusat kegiatan penduduk yang didukung dengan fasilitas layanan transportasi. Misalnya, fasilitas transportasi untuk kawasan permukiman dan kawasan perdagangan.
Kedua, sistem jaringan, yakni bagaimana membangun sistem jaringan dan simpul-simpul fasilitas transportasi yang melayani jaringan jalan, jaringan kereta api, dan angkutan umum.
Ketiga, sistem pergerakan untuk mengantisipasi bangkitan pergerakan orang dan barang berdasarkan jumlah, tujuan, lokasi, dan waktu perjalanan.
Ketiga sistem tersebut saat ini, baik secara kelembagaan maupun rencana program di tingkat nasional dan daerah, seperti tidak kompak dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.
Kebijakan transportasi massal di Jakarta pun tidak mampu berjalan optimal karena tekanan eksternal kebijakan industri otomotif. Maka, justru kemacetan yang menjadi-jadi dengan peningkatan penjualan mobil dan motor pribadi yang tanpa henti.
Kompleksitas masalah Jakarta tidak boleh dibiarkan berlarut. Tanpa perbaikan, Jakarta akan dipandang sebagai kota penuh masalah, dan statusnya sebagai ibu kota negara dalam perspektif tertentu tidak jauh berbeda dengan ibu kota provinsi lainnya.
Jika ada kota lain yang sanggup mengajukan diri sebagai calon ibu kota negara, secara politik daya tarik kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional akan segera memudar.
Maka, realitas masalah yang harus kita selesaikan saat ini adalah melakukan percepatan solusi dengan fokus pada derita yang paling dirasakan warga. Hentikan wacana yang penuh kontroversi supaya energi dan waktu tidak habis sebatas diskusi.[kompas]


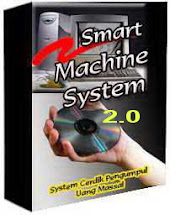

0 komentar:
Posting Komentar